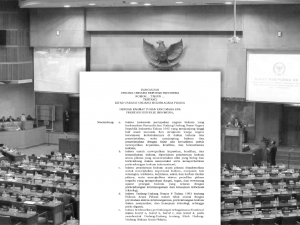Jakarta, Wartajiwa.com – Belum genap enam bulan menjalani sanksi etik dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Ahmad Sahroni resmi kembali menduduki kursi Wakil Ketua Komisi III DPR RI pada Kamis (19/2/2026). Penetapan yang dilakukan dalam rapat pleno Komisi III ini menuai kritik tajam, karena dianggap mengabaikan esensi penegakan etik dan menunjukkan betapa murahnya akuntabilitas di parlemen Indonesia.
Yang lebih menyakitkan, kembalinya Sahroni seolah mengukuhkan bahwa negara telah melupakan 12 warga yang meninggal dalam demonstrasi Agustus 2025—termasuk Affan Kurniawan yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Sementara korban dan keluarganya masih menanti keadilan, politisi yang pernah menyebut pengkritik DPR sebagai “orang tolol sedunia” justru kembali ke posisi strategis yang membidangi hukum dan keamanan.
Ini bukan sekadar soal satu individu. Ini tentang sistem yang memilih melindungi elite politik daripada menghormati rasa keadilan masyarakat.
Sanksi Dikebiri Interpretasi
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan penetapan Sahroni berdasarkan surat resmi Fraksi Partai NasDem tertanggal 12 Februari 2026. Seluruh anggota Komisi III yang hadir menyetujui secara aklamasi, seolah tidak ada yang salah dengan penunjukan ini.
Masalahnya, MKD DPR telah menjatuhkan sanksi penonaktifan selama enam bulan kepada Sahroni pada 5 November 2025. Dalam putusannya, MKD menyatakan sanksi dihitung sejak Sahroni dinonaktifkan oleh Dewan Pimpinan Partai (DPP) NasDem pada 1 September 2025. Artinya, jika dihitung secara konsisten, masa sanksi seharusnya berakhir pada akhir Februari atau awal Maret 2026—bukan pertengahan Februari.
Peneliti Indonesia Parliamentary Center (IPC) Arif Adiputro menegaskan bahwa pengangkatan Sahroni berpotensi melanggar Pasal 106 UU MD3 yang mengatur bahwa anggota DPR yang nonaktif tidak boleh menjalankan tugas sebagai anggota parlemen, termasuk menduduki jabatan pimpinan komisi selama masa penonaktifan.
“DPR mungkin berdalih bahwa penetapan ini bersifat administratif dan tidak langsung mengaktifkan Sahroni secara penuh hingga masa sanksi berakhir, tapi ini terasa seperti pembenaran lemah,” kata Arif. Ia menduga DPR sengaja melonggarkan interpretasi perhitungan periode sanksi demi memprioritaskan stabilisasi fraksi NasDem di komisi strategis seperti Komisi III.
Wakil Ketua Partai NasDem Saan Mustopa membela keputusan ini dengan argumen bahwa Sahroni telah menyelesaikan sanksinya. “Jadi kalau misalnya pimpinan DPR sudah menetapkan, berarti kan di MKD sudah tidak masalah,” ujarnya. Logika lingkaran ini menunjukkan betapa rendahnya standar akuntabilitas: sanksi dianggap selesai bukan karena waktu yang tuntas dijalani, melainkan karena ada keputusan politik untuk mengembalikan jabatannya.
“Tolol” yang Tak Terhapuskan
Sahroni dijatuhi sanksi MKD bukan tanpa alasan. Pada 22 Agustus 2025, di tengah gelombang protes publik terhadap tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan, Sahroni melontarkan pernyataan yang memicu kemarahan masif: “Mental manusia yang begitu adalah mental manusia tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia.”
Pernyataan arogan ini langsung memantik kemarahan publik. Demonstrasi yang tadinya terkendali berubah menjadi gelombang aksi di berbagai kota. Rumah Sahroni di Tanjung Priok bahkan digeruduk dan dijarah massa pada 30 Agustus 2025—menunjukkan betapa dalamnya kemarahan rakyat terhadap sikap merendahkan wakil rakyat tersebut.
MKD menilai Sahroni seharusnya merespons desakan pembubaran DPR dengan pemilihan kata yang pantas dan bijaksana, bukan dengan diksi yang menghina dan merendahkan masyarakat. Namun, Sahroni tidak pernah benar-benar meminta maaf. Ia justru mengunggah gambar orang bertopeng anonim dengan narasi “Makin banyak orang tolol yang bangga akan ketololannya”—seolah mempertahankan posisinya.
Partai NasDem kemudian menonaktifkan Sahroni pada 1 September 2025 dan menggantikannya dengan Rusdi Masse Mappasessu di Komisi III. Namun, ketika Rusdi memutuskan hijrah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI), kursi Wakil Ketua Komisi III kembali kosong—dan NasDem memilih mengembalikan Sahroni, bukan mencari figur yang lebih kredibel.
12 Nyawa yang Dilupakan
Yang paling menyakitkan dari kembalinya Sahroni adalah konteksnya: demonstrasi Agustus 2025 yang berujung pada kematian 12 warga sipil seolah telah dilupakan. Affan Kurniawan, pengemudi ojek online berusia 21 tahun yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob pada malam 28 Agustus 2025, menjadi katalis yang mengubah dinamika massa secara dramatis.
Komisi Pencari Fakta (KPF) yang dibentuk oleh koalisi masyarakat sipil menegaskan bahwa kematian Affan bukan kecelakaan, melainkan pembunuhan. Kendaraan rantis Brimob melindas Affan dua kali—lindasan pertama ketika Affan terjatuh, kemudian setelah berhenti tujuh detik, kendaraan kembali melaju dan melindas untuk kedua kalinya. Affan dinyatakan meninggal pukul 19.58 WIB di RSCM.
Selain Affan, ada 11 korban lainnya: Septinus Sesa, Iko Juliant Junior, Andika Luthfi Falah, Syaiful Akbar, Muhammad Akbar Basri, Sarinawati, Rusdamdiansyah, Rheza Sendy Pratama, Sumari, Muhammad Farhan Hamid, dan Reno Syahputradewo. Sebagian tewas akibat kekerasan aparat, sebagian lagi menjadi korban kerusuhan yang dipicu oleh kemarahan atas kematian Affan dan sikap arogan para anggota DPR—termasuk Sahroni.
Hingga kini, proses hukum terhadap anggota Brimob yang melindas Affan masih bergulir tanpa kepastian. Komandan kendaraan, Kompol Cosmas Kaju Gae, hanya dipecat dari kepolisian. Pengemudi kendaraan, Bripka Rohmat, hanya didemosi selama tujuh tahun. Lima anggota Brimob lainnya yang berada di dalam kendaraan hanya diminta menyampaikan permohonan maaf secara lisan dan tertulis—tanpa sanksi pidana yang berarti.
Sementara keluarga korban masih menanti keadilan, sementara 703 orang yang ditahan sebagai “tahanan politik” dalam laporan KPF masih berjuang membuktikan mereka bukan provokator, Ahmad Sahroni—yang pernyataannya turut memantik kemarahan publik—justru kembali ke kursi kekuasaan.
Komisi III: Ironi yang Menyakitkan
Yang membuat kembalinya Sahroni semakin problematis adalah posisi yang ia duduki: Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Komisi ini seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawasi penegakan hukum dan melindungi hak-hak warga negara.
Bagaimana mungkin seorang politisi yang pernah merendahkan rakyat dengan sebutan “tolol,” kini duduk di posisi yang seharusnya mengawasi kepolisian—institusi yang bertanggung jawab atas kematian Affan Kurniawan?
Ironi ini semakin tajam ketika mengingat bahwa Sahroni pernah dikenal sebagai politisi yang vokal menuntut hukuman tegas bagi pengedar narkoba. Namun, ketika rakyat menuntut akuntabilitas atas kematian warga sipil di tangan aparat, ia justru menyebut mereka “tolol.” Standar ganda ini menunjukkan bahwa Sahroni lebih peduli pada citra sebagai penegak hukum ketimbang esensi keadilan itu sendiri.
IPC menilai bahwa rentetan polemik DPR soal Sahroni menunjukkan kultur politik di parlemen masih sangat patrimonial. Keputusan DPR lebih fokus pada distribusi kekuasaan dan stabilitas fraksi ketimbang pada akuntabilitas etik dan kepercayaan publik.
Pola yang Berulang
Kembalinya Sahroni bukan kasus tunggal. Adies Kadir, Wakil Ketua DPR yang juga dinonaktifkan sementara akibat pernyataannya yang kontroversial selama demonstrasi Agustus 2025, kini justru dipilih DPR untuk menjadi Hakim Konstitusi. Sementara Nafa Urbach dan Eko Patrio, yang juga dijatuhi sanksi MKD, telah kembali aktif sebagai anggota DPR setelah masa sanksi mereka berakhir.
Pola ini menunjukkan bahwa sanksi etik di DPR hanyalah formalitas. Tidak ada konsekuensi jangka panjang bagi anggota dewan yang melanggar kode etik, selama mereka masih memiliki dukungan politik di fraksinya. Sistem ini tidak dirancang untuk mengubah perilaku atau mengembalikan kepercayaan publik, melainkan hanya untuk meredam kemarahan sementara hingga perhatian publik beralih.
Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun pernah menyatakan bahwa salah satu pertimbangan yang meringankan hukuman Sahroni adalah peristiwa penjarahan terhadap rumahnya di Tanjung Priok pada Agustus lalu. Logika ini terbalik: penjarahan terjadi justru karena pernyataan Sahroni yang memicu kemarahan publik. Menjadikan akibat dari perbuatan sebagai alasan peringanan hukuman adalah bentuk victim blaming terhadap rakyat yang marah atas kesombongan wakilnya.
Keadilan untuk Siapa?
Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: untuk siapa sebenarnya sistem ini bekerja? Ketika seorang politisi yang pernyataannya turut memicu kerusuhan dapat kembali ke posisi kekuasaan hanya dalam waktu kurang dari enam bulan, sementara keluarga korban masih menanti keadilan, sementara ratusan aktivis masih menjadi tahanan politik, sementara aparat yang melindas Affan hanya mendapat sanksi administratif—sistem ini jelas tidak bekerja untuk rakyat.
Sahroni sendiri, dalam pernyataannya seusai dilantik, mengucapkan terima kasih kepada MKD yang “telah menyidangkan saya dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya.” Tidak ada ungkapan penyesalan yang mendalam. Tidak ada pengakuan bahwa pernyataannya telah menyakiti rakyat. Tidak ada empati terhadap 12 korban yang meninggal dan ratusan lainnya yang menjadi korban kerusuhan yang dipicu oleh arogansi para anggota DPR.
Yang ada hanyalah harapan klise untuk “menjadi lebih baik”—tanpa introspeksi yang tulus tentang apa yang telah ia perbuat dan bagaimana ia seharusnya bertanggung jawab.
CATATAN REDAKSI:
Wartajiwa.com mencatat bahwa kembalinya Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menunjukkan betapa lemahnya penegakan etik di parlemen Indonesia. Sanksi yang dijatuhkan MKD ternyata hanya formalitas untuk meredam kemarahan publik sementara, bukan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat atau mengubah perilaku pelanggar.
Yang lebih menyakitkan, kembalinya Sahroni terjadi ketika 12 korban jiwa demonstrasi Agustus 2025—termasuk Affan Kurniawan yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob—masih menanti keadilan. Sementara keluarga korban masih berduka, sementara ratusan aktivis masih menjadi tahanan politik, sementara aparat yang melindas Affan hanya mendapat sanksi administratif, politisi yang pernyataannya turut memicu kerusuhan justru kembali ke posisi kekuasaan.
Redaksi mendesak DPR untuk mengembalikan esensi sanksi etik sebagai instrumen akuntabilitas, bukan sekadar alat politik untuk stabilisasi fraksi. Komisi III yang membidangi hukum dan HAM seharusnya dipimpin oleh figur yang memiliki integritas dan kepekaan terhadap rasa keadilan masyarakat—bukan oleh politisi yang pernah merendahkan rakyat dan kini kembali tanpa pertanggungjawaban yang tulus.
Sistem parlemen yang tidak menghargai suara rakyat dan melindungi elite politik di atas segalanya hanya akan semakin memperdalam krisis kepercayaan publik. Rakyat tidak akan melupakan. Rakyat masih menuntut keadilan untuk 12 nyawa yang melayang—dan akuntabilitas bagi mereka yang turut bertanggung jawab atas tragedi tersebut.
Penuli: Atma Guritno
Editor: Vincencius Vino